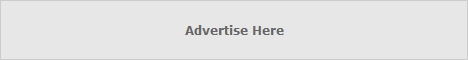PC Siswantoko
Peserta Program Pascasarjana Academia Alfonsiana,
Pontificia Universita Lateranense, Roma
Selasa, 23 Mei 2006
Diunduh dari : http://www.semipalar.net/artikel/artikel33.html pada 31 Mei 2009 : 3 : 25 WIBsumber : www.gatago.com
Standar ujian nasional sedang menjadi topik diskusi hangat antara pemerintah dan DPR. Bahkan Komisi X DPR mendesak pemerintah merevisi PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pertentangan antarpasal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional serta adanya kesenjangan mutu pendidikan antardaerah adalah dua alasan mendasar di
balik desakan revisi itu (Kompas Online, 11/5/2006). Perdebatan itu menambah panjang deret ketidakstabilan sistem pendidikan nasional.
Paradigma pendidikan
Meski pemerintah harus bertanggung jawab atas mutu pendidikan nasional, pihak yang paling tahu tentang mutu dan kemampuan anak didik adalah pendidik. Dengan demikian, tugas dan hak pendidiklah untuk memberi penilaian. Penetapan standar nasional untuk kelulusan mengandaikan mutu pendidikan di tiap daerah sama. Kenyataannya, masih ada jurang perbedaan antara proses pendidikan di kota dan desa, bahkan antarprovinsi dan pulau.
Penetapan batas minimal kelulusan 4,5 memberi gambaran, pemerintah memandang proses pendidikan hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan yang bisa mudah diukur dengan angka. Penetapan itu mereduksi makna pendidikan sebagai sebuah proses pematangan pribadi mencakup pengembangan, kognisi, afeksi, mental, dan kepribadian.
John Dewey dalam buku Education and Democracy (1916) telah mendengungkan konsep pendidikan integral berdasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik. Pendidikan yang berbasis realitas dan pengalaman anak didik sebenarnya bentuk perlawanan dan kritik pada pola-pola pendidikan tradisional yang hanya memindahkan ilmu pengetahuan masa lampau kepada tiap generasi baru.
Pendidikan tidak dimaksud sekadar mencetak orang yang pandai menghafal dan berhitung, tetapi melahirkan orang-orang berpribadi matang. Pendidikan tidak hanya tempat mengasah ketajaman otak, tetapi tempat menyemai nilai-nilai dasar kehidupan guna menggapai masa depan dan hidup bermasyarakat. Bangsa Indonesia amat membutuhkan sistem pendidikan seperti itu, terutama untuk melahirkan generasi muda yang tangguh dan bertanggung jawab, dan mampu memperbaiki kehidupan bangsa
ini.
Maka, kengototan pemerintah untuk tetap melangsungkan ujian dengan standar nasional, hanya karena ingin mendorong peserta didik bekerja keras, tidak akan memberi dampak positif berkelanjutan bagi kematangan dan kemandirian peserta didik. Bahkan standar itu tidak representatif sebagai titik acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan bangsa ini.
Sementara revisi pasal-pasal PP No 19/2005, sebagaimana didesakkan DPR, tidak akan berarti bila tidak ada pembaruan dan rekonstruksi terhadap paradigma pendidikan.
Tugas pemerintah
Dalam konteks pendidikan holistik, pemerintah tidak perlu mengambil alih peran pendidik dengan menetapkan standar pendidikan sebab pemerintah tidak berhubungan langsung dengan peserta didik. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan sistem pendidikan yang efektif, integral, dan mengembangkan pendidik maupun peserta didik.
Pertama, pemerataan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Di banyak daerah sarana dan prasarana pendidikan amat memprihatinkan. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman, banyak gedung sekolah tak layak pakai, dan penggemblengan mental pengabdian pendidik, merupakan pekerjaan besar yang harus diprioritaskan dan dituntaskan pemerintah.
Amat tidak masuk akal bila pemerintah tiba-tiba menetapkan standar kelulusan secara nasional, sementara pembangunan dan pemajuan pendidikan masih amat parsial.
Kedua, perubahan sistem pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini amat memungkinkan pihak sekolah untuk bereksplorasi, baik dalam program maupun kurikulum yang benar-benar kontekstual, yaitu berdasarkan pada kebutuhan anak didik dan menyatu dengan budaya dan karakter setempat. Jadi standar penilaian terletak pada tingkat penambahan pengetahuan serta pengembangan kepribadian, seperti menghargai orang lain, menghormati perbedaan, kedisiplinan, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.
Ketiga, proses pendidikan yang holistik juga menuntut adanya budaya belajar di kalangan masyarakat. Dengan demikian, proses pendidikan tidak dapat dikotakkan dalam pendidikan formal belaka, tetapi perlu dibuat sistem pendidikan berkesinambungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ritme kehidupan masyarakat sebab masyarakat menentukan proses pendidikan melalui nilai- nilai dan strukturnya. Sebaliknya pendidikan menyumbangkan nilai-nilai untuk perubahan masyarakat. Membangun budaya membaca di masyarakat bisa dijadikan titik berangkat untuk membangun budaya belajar ini.
Berkembang tidaknya sistem pendidikan bangsa, tidak terletak pada standar ujian nasional diberlakukan atau jadi tidaknya PP No 19/2005 direvisi, tetapi pada lahir tidaknya sistem pendidikan baru yang mengembangkan nilai- nilai hakiki kemanusiaan. Selama proses pendidikan tetap bermodel pengajaran, transfer ilmu, dunia pendidikan hanya melahirkan orang-orang pintar tetapi belum tentu benar, ahli tetapi belum tentu rendah hati, cerdas tetapi belum tentu bijaksana.
Peserta Program Pascasarjana Academia Alfonsiana,
Pontificia Universita Lateranense, Roma
Selasa, 23 Mei 2006
Diunduh dari : http://www.semipalar.net/artikel/artikel33.html pada 31 Mei 2009 : 3 : 25 WIBsumber : www.gatago.com
Standar ujian nasional sedang menjadi topik diskusi hangat antara pemerintah dan DPR. Bahkan Komisi X DPR mendesak pemerintah merevisi PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pertentangan antarpasal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional serta adanya kesenjangan mutu pendidikan antardaerah adalah dua alasan mendasar di
balik desakan revisi itu (Kompas Online, 11/5/2006). Perdebatan itu menambah panjang deret ketidakstabilan sistem pendidikan nasional.
Paradigma pendidikan
Meski pemerintah harus bertanggung jawab atas mutu pendidikan nasional, pihak yang paling tahu tentang mutu dan kemampuan anak didik adalah pendidik. Dengan demikian, tugas dan hak pendidiklah untuk memberi penilaian. Penetapan standar nasional untuk kelulusan mengandaikan mutu pendidikan di tiap daerah sama. Kenyataannya, masih ada jurang perbedaan antara proses pendidikan di kota dan desa, bahkan antarprovinsi dan pulau.
Penetapan batas minimal kelulusan 4,5 memberi gambaran, pemerintah memandang proses pendidikan hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan yang bisa mudah diukur dengan angka. Penetapan itu mereduksi makna pendidikan sebagai sebuah proses pematangan pribadi mencakup pengembangan, kognisi, afeksi, mental, dan kepribadian.
John Dewey dalam buku Education and Democracy (1916) telah mendengungkan konsep pendidikan integral berdasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik. Pendidikan yang berbasis realitas dan pengalaman anak didik sebenarnya bentuk perlawanan dan kritik pada pola-pola pendidikan tradisional yang hanya memindahkan ilmu pengetahuan masa lampau kepada tiap generasi baru.
Pendidikan tidak dimaksud sekadar mencetak orang yang pandai menghafal dan berhitung, tetapi melahirkan orang-orang berpribadi matang. Pendidikan tidak hanya tempat mengasah ketajaman otak, tetapi tempat menyemai nilai-nilai dasar kehidupan guna menggapai masa depan dan hidup bermasyarakat. Bangsa Indonesia amat membutuhkan sistem pendidikan seperti itu, terutama untuk melahirkan generasi muda yang tangguh dan bertanggung jawab, dan mampu memperbaiki kehidupan bangsa
ini.
Maka, kengototan pemerintah untuk tetap melangsungkan ujian dengan standar nasional, hanya karena ingin mendorong peserta didik bekerja keras, tidak akan memberi dampak positif berkelanjutan bagi kematangan dan kemandirian peserta didik. Bahkan standar itu tidak representatif sebagai titik acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan bangsa ini.
Sementara revisi pasal-pasal PP No 19/2005, sebagaimana didesakkan DPR, tidak akan berarti bila tidak ada pembaruan dan rekonstruksi terhadap paradigma pendidikan.
Tugas pemerintah
Dalam konteks pendidikan holistik, pemerintah tidak perlu mengambil alih peran pendidik dengan menetapkan standar pendidikan sebab pemerintah tidak berhubungan langsung dengan peserta didik. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan sistem pendidikan yang efektif, integral, dan mengembangkan pendidik maupun peserta didik.
Pertama, pemerataan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan. Di banyak daerah sarana dan prasarana pendidikan amat memprihatinkan. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman, banyak gedung sekolah tak layak pakai, dan penggemblengan mental pengabdian pendidik, merupakan pekerjaan besar yang harus diprioritaskan dan dituntaskan pemerintah.
Amat tidak masuk akal bila pemerintah tiba-tiba menetapkan standar kelulusan secara nasional, sementara pembangunan dan pemajuan pendidikan masih amat parsial.
Kedua, perubahan sistem pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini amat memungkinkan pihak sekolah untuk bereksplorasi, baik dalam program maupun kurikulum yang benar-benar kontekstual, yaitu berdasarkan pada kebutuhan anak didik dan menyatu dengan budaya dan karakter setempat. Jadi standar penilaian terletak pada tingkat penambahan pengetahuan serta pengembangan kepribadian, seperti menghargai orang lain, menghormati perbedaan, kedisiplinan, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.
Ketiga, proses pendidikan yang holistik juga menuntut adanya budaya belajar di kalangan masyarakat. Dengan demikian, proses pendidikan tidak dapat dikotakkan dalam pendidikan formal belaka, tetapi perlu dibuat sistem pendidikan berkesinambungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ritme kehidupan masyarakat sebab masyarakat menentukan proses pendidikan melalui nilai- nilai dan strukturnya. Sebaliknya pendidikan menyumbangkan nilai-nilai untuk perubahan masyarakat. Membangun budaya membaca di masyarakat bisa dijadikan titik berangkat untuk membangun budaya belajar ini.
Berkembang tidaknya sistem pendidikan bangsa, tidak terletak pada standar ujian nasional diberlakukan atau jadi tidaknya PP No 19/2005 direvisi, tetapi pada lahir tidaknya sistem pendidikan baru yang mengembangkan nilai- nilai hakiki kemanusiaan. Selama proses pendidikan tetap bermodel pengajaran, transfer ilmu, dunia pendidikan hanya melahirkan orang-orang pintar tetapi belum tentu benar, ahli tetapi belum tentu rendah hati, cerdas tetapi belum tentu bijaksana.